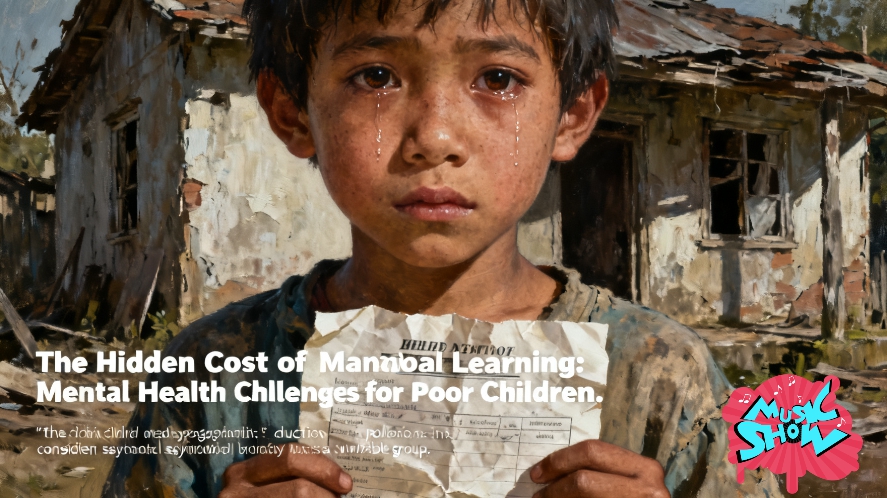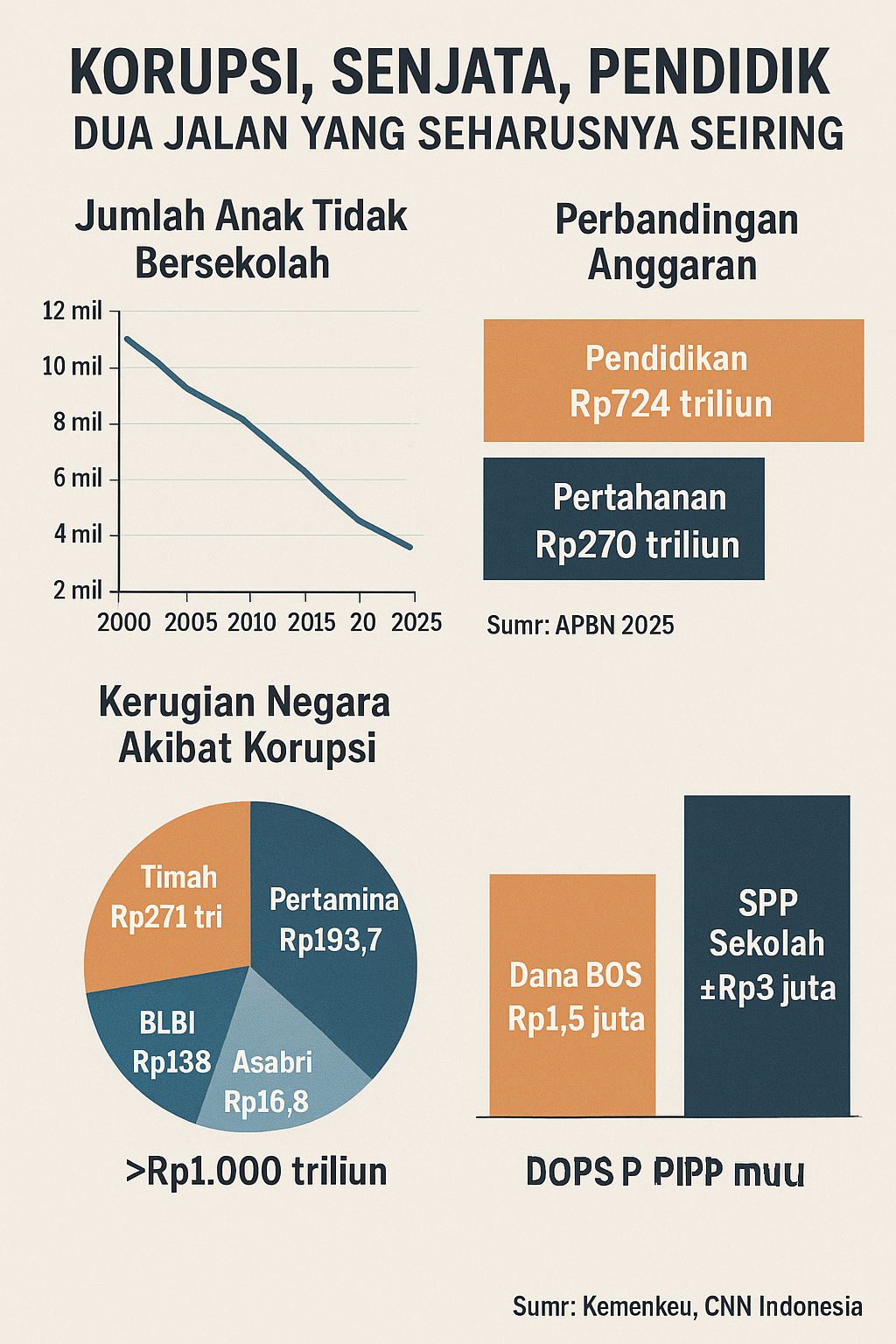Ketika Wajib Belajar Menekan Anak Miskin: Negara Hadir, tapi Psikologi Mereka Terabaikan
Jingga News – Wajib belajar selama ini diposisikan sebagai simbol kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan setiap warga. Dalam dokumen kebijakan, program ini dipresentasikan sebagai upaya pemerataan akses dan pembangunan sumber daya manusia. Namun di balik narasi tersebut, terdapat realitas yang jarang dibahas secara serius: dampak wajib belajar terhadap psikologi anak miskin.
Bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekolah bukan sekadar ruang belajar. Ia adalah ruang sosial yang penuh tuntutan, perbandingan, dan tekanan emosional. Ketika negara mewajibkan pendidikan tanpa sepenuhnya memastikan kebutuhan dasarnya, beban kebijakan itu tidak berhenti pada orang tua, melainkan masuk ke wilayah paling rapuh: kesehatan mental anak.
Wajib Belajar sebagai Kebijakan Administratif
Dari perspektif kebijakan publik, kebijakan pendidikan sering dirancang dengan pendekatan administratif. Negara memastikan ketersediaan sekolah, kurikulum, dan tenaga pendidik. Biaya pendidikan dasar dinyatakan gratis, sementara kebutuhan lain dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat.
Secara administratif, pendekatan ini tampak rasional. Namun pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa semua keluarga memiliki kapasitas ekonomi yang relatif setara. Dalam kenyataannya, asumsi ini tidak pernah benar-benar berlaku, terutama bagi keluarga miskin yang hidup dengan keterbatasan struktural.
Akibatnya, wajib belajar di Indonesia sering kali dijalankan sebagai kewajiban formal tanpa perlindungan psikologis yang memadai bagi anak-anak dari kelompok rentan.
Kemiskinan dan Lingkungan Psikologis Anak
Dalam kajian psikologi perkembangan, kemiskinan tidak dipahami semata sebagai kekurangan materi, melainkan sebagai chronic stress environment—lingkungan yang menciptakan tekanan berkepanjangan. Anak yang tumbuh dalam keluarga miskin terpapar kecemasan ekonomi, ketidakpastian, dan keterbatasan pilihan sejak dini.
Kondisi ini memengaruhi emotional regulation dan pembentukan self-concept. Ketika anak memasuki sekolah, ia membawa seluruh konteks psikologis tersebut. Sekolah kemudian menjadi ruang pembanding sosial yang intens, di mana standar yang sama diterapkan tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi.
Bagi anak yang tidak mampu membeli buku, alat tulis, atau memenuhi kebutuhan sekolah lainnya, sekolah berpotensi berubah dari ruang pembelajaran menjadi sumber tekanan psikologis.
Internalisasi Kekurangan dan Kerentanan Mental
Anak belum memiliki kapasitas kognitif untuk memahami kemiskinan sebagai masalah struktural. Secara psikologis, mereka cenderung melakukan internalization, yakni menyerap kegagalan eksternal sebagai kegagalan pribadi.
Tidak mampu membeli buku atau perlengkapan sekolah sering dimaknai sebagai tanda bahwa dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup rajin, atau tidak pantas berada di sekolah. Proses ini merusak harga diri dan melemahkan motivasi belajar.
Dalam konteks ini, pendidikan dan kemiskinan tidak lagi sekadar persoalan akses, melainkan persoalan martabat dan identitas diri anak.
Rasa Malu dan Tekanan Sosial di Sekolah
Salah satu emosi paling dominan yang dialami anak miskin di sekolah adalah rasa malu. Dalam psikologi, rasa malu (shame) berbeda dari rasa bersalah (guilt). Rasa bersalah berkaitan dengan tindakan, sementara rasa malu menyasar identitas diri.
Teguran karena tidak membawa buku, sindiran soal seragam, atau pengucilan karena tidak membayar iuran sering dimaknai anak sebagai penilaian terhadap dirinya sebagai pribadi. Rasa malu yang berulang dapat memicu social withdrawal, kecemasan, dan gejala depresi.
Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan mental tidak bisa dipisahkan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Beban Emosional dan Perasaan Menjadi Beban Keluarga
Anak dari keluarga miskin sering mengalami emotional parentification. Mereka menyadari keterbatasan orang tua dan berusaha menekan kebutuhan pribadi agar tidak menambah beban keluarga.
Dalam konteks sekolah, kondisi ini menciptakan konflik batin. Anak memahami pentingnya pendidikan, tetapi juga memahami konsekuensi ekonomi dari setiap kebutuhan sekolah. Dari sini muncul perasaan bersalah, cemas, dan dalam kasus tertentu, keyakinan keliru bahwa keberadaan dirinya justru menyulitkan keluarga.
Dalam kajian psikologi klinis, perasaan menjadi beban merupakan faktor risiko serius bagi gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja.
Kebijakan Netral yang Tidak Netral
Secara formal, pemisahan antara biaya pokok dan biaya tambahan terlihat netral. Namun dalam praktik, kebijakan ini menciptakan ketimpangan nyata. Bagi anak miskin, biaya tambahan justru menjadi sumber tekanan utama.
Dari perspektif psikologi sosial, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk structural violence non-fisik: sistem tidak melukai secara langsung, tetapi menciptakan tekanan yang merusak kesejahteraan mental.
Dalam situasi ini, peran negara dalam pendidikan dipertanyakan, bukan karena negara absen sepenuhnya, tetapi karena kehadirannya bersifat administratif, bukan manusiawi.
Dampak Jangka Panjang terhadap Mobilitas Sosial
Tekanan psikologis selama masa sekolah memiliki dampak jangka panjang. Anak yang tumbuh dengan rasa tidak layak cenderung memiliki aspirasi pendidikan rendah, enggan bersaing, dan kurang percaya pada institusi.
Alih-alih memutus rantai kemiskinan, kebijakan wajib belajar yang mengabaikan psikologi anak justru berpotensi mereproduksi ketimpangan dalam sistem pendidikan.
Menuju Wajib Belajar yang Berkeadilan
Jika negara ingin menjadikan wajib belajar sebagai instrumen keadilan sosial, maka pendekatan psikologis harus menjadi bagian dari desain kebijakan. Ini mencakup jaminan kebutuhan dasar, penghapusan praktik yang mempermalukan, dan pengakuan bahwa hak pendidikan anak mencakup perlindungan kesehatan mental.
Keterbatasan anggaran mungkin tidak terhindarkan. Namun yang paling merusak psikologi anak bukan keterbatasan tersebut, melainkan tuntutan moral tanpa perlindungan nyata.
Penutup
Pendidikan bukan hanya proses kognitif, tetapi juga pengalaman emosional. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya belajar membaca dan berhitung, mereka belajar tentang posisi mereka di masyarakat.
Ketika kebijakan wajib belajar mengabaikan dimensi psikologis ini, sekolah berisiko menjadi ruang reproduksi luka batin. Negara tidak cukup hanya hadir secara administratif; negara harus hadir secara empatik.
Pendidikan sebagai keadilan sosial hanya mungkin terwujud jika kebijakan tidak melukai martabat dan kesehatan mental anak-anak yang paling rentan.